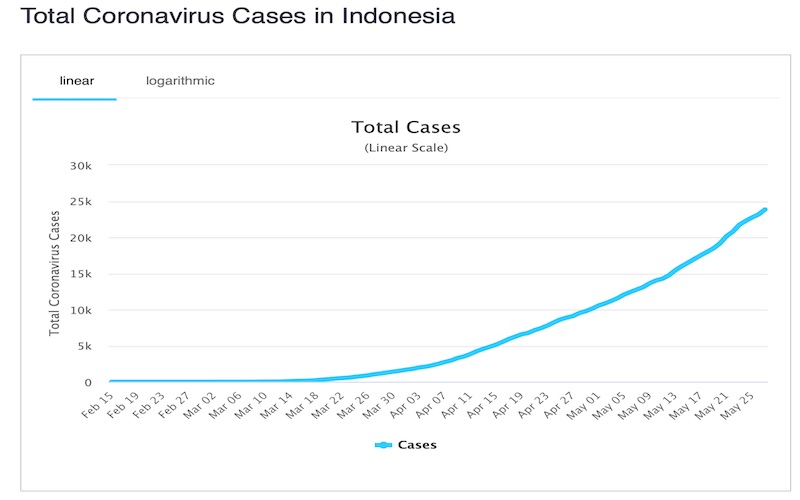Bisnis.com, JAKARTA - Gara-gara wabah Covid-19, istilah ini tiba-tiba populer: new normal. Banyak orang menyebutnya, mulai dari pejabat teras hingga rakyat jelata. Sampai-sampai banyak yang bingung pula, binatang apa sesungguhnya.
Sejatinya, istilah new normal merujuk pada situasi baru yang membentuk perilaku baru. Keadaan yang tiba-tiba berubah, lalu menciptakan kebiasaan baru.
New normal dimaknai sebagai keadaan saat ini, setelah beberapa perubahan dramatis telah terjadi. New normal adalah situasi tak biasa, yang menggantikan keadaan yang biasa.
New normal alias normal baru mendorong seseorang untuk menerima kejadian yang sebelumnya tidak biasa, kini menjadi hal biasa.
Saya coba menengok Oxford Dictionary melalui Mbah Google, begitu mesin pencari ini biasa dijuluki. Kamus itu menyebut "the new normal" sebagai "a previously unfamiliar or atypical situation that has become standard, usual, or expected."
Intinya, situasi yang sebelumnya tidak dikenal atau tidak biasa, lalu (kini) telah menjadi standard, menjadi biasa, atau bahkan menjadi yang diharapkan.
Baca Juga
Dalam konteks wabah Covid-19, situasi kehidupan saat ini sebenarnya sangatlah tidak biasa alias tidak normal. Itu bila merujuk kepada situasi sebelum Covid-19. Merujuk pada kebiasaan-kebiasaan sebelumnya.
Orang tinggal di rumah, tidak melakukan aktivitas rutin yang sebelumnya dilakukan di luar rumah. Tidak sekolah. Tidak pergi ke tempat ibadah. Tidak dine-in di restoran, cukup pesan antar atau take-away.
Juga tidak jalan-jalan pelesiran. Bahkan tidak pergi ke kantor, melainkan kerja dari rumah. Istilah keren-nya: work from home.
Kebiasaan semacam itu, sebelum pandemi Covid-19, pasti dianggap tidak normal. Di masa lalu, seorang karyawan yang bekerja dari rumah, meski outcome atau hasil unjuk kerjanya jelas, pasti dipersalahkan oleh Manajer HRD.
Dulu, tidak absen ke kantor berarti tidak masuk kerja. Begitu kira-kira.
Sebelum wabah Covid-19, yang disebut bekerja di kebanyakan perusahaan adalah kalau Anda datang ke kantor dan tempelin jari ke mesin absensi. Sah!
Maafkan, terpaksa saya pinjam satu kata bertanda seru itu. Kata tersebut belakangan kerap menjadi bagian dari judul berita bombastis banyak media online.
Bahwa karyawan tersebut di kantor lebih produktif atau tidak, itu soal lain. Yang penting ke kantor, dan absen. Itu yang normal.
Tapi itu dulu. Nah, sekarang situasi berubah. Dunia berubah.
Demi mencegah penularan Covid-19 yang lebih luas, orang tidak datang ke kantor, melainkan kerja dari rumah. Apalagi orang takut sakit. Dan takut mati.
Maka pasca Covid nanti, bisa jadi sebagian kebiasaan tersebut akan tetap dilakukan. Jadilah ia new normal. Situasi normal baru.
Bagi banyak orang, pandemi Covid-19 ini dianggap sebagai disruptor kehidupan yang paling tragis. Akibatnya telah menghasilkan situasi normal baru yang jauh berbeda dari sebelumnya.
Bisa jadi kehidupan sehari-hari akan berubah drastis. Yang biasanya cuek tidak pakai masker, sekarang menjadikan masker sebagai aksesori wajib saat keluar rumah.
Bisa jadi pula, hand sanitizer akan menjadi bekal wajib saat bepergian. Ritual cium pipi kiri-kanan barangkali akan ditinggalkan oleh sebagian kalangan.
Driver taksi, boleh jadi, akan memasang kaca pembatas dengan penumpang (seperti di Hong Kong dan Jepang), agar "terisolasi" dari kemungkinan terpapar droplet atau percikan penumpang manakala batuk atau bersin.
Tapi bukan cuma rutinitas harian semacam itu. Pola kerja boleh jadi akan banyak berubah. Bisnis juga berubah, karena perubahan perilaku konsumen yang menjalani kehidupan normal baru.
Sekadar contoh, saat ini rapat virtual dalam sehari bisa dilakukan sampai 5 kali dari berbagai peserta dan lokasi berbeda dengan memanfaatkan teknologi "web-conference" berbagai aplikasi.
Zoom meeting saat ini menjadi yang paling populer. Telkomsel memiliki Cloud-X. Juga ada Team dari Microsoft serta Skype yang telah lebih dulu eksis.
Aneka "seminar" bahkan halal bihalal keluarga atau komunitas dari berbagai daerah pun saat ini banyak difasilitasi dengan teknologi "virtual meeting" tersebut.
***
Dalam konteks ekonomi, istilah new normal pertama kali muncul saat krisis keuangan 2008. Lalu mencuat kembali saat krisis komoditas 2012, dan belakangan ini pandemi Covid-19.
Istilah itu digunakan untuk menyiratkan bahwa sesuatu yang sebelumnya dinilai "tidak normal" telah "menjadi biasa". Misalnya setelah crash harga komoditas pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih rendah dianggap sebagai normal baru.
Ekonomi China yang dulu pernah tumbuh di atas 10%, belakangan hanya tumbuh di kisaran 6%, dianggap sebagai pertumbuhan normal baru.
Begitu pula ekonomi Indonesia yang dulu pernah tumbuh di atas 7%, lalu beberapa tahun terakhir hanya tumbuh di kisaran 5%, juga dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi normal baru.
Dan hari ini, pandemi Covid-19 kian mengubah dunia. Pandemi ini telah dan akan men-drive perubahan ekonomi, terlebih difasilitasi oleh perkembangan teknologi yang pesat akhir-akhir ini.
Dalam sebuah kesempatan, saya beroleh cerita dari Prof. Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Riset dan Teknologi, ihwal new normal pasca pandemi Covid-19 tersebut.
Menurut Prof. Bambang, keadaan new normal dalam konteks kehidupan post-Covid-19 adalah kombinasi antara pelaksanaan protokol kesehatan oleh masyarakat dan perilaku ekonomi digital.
Prof Bambang menyebutnya sebagai less-contact economy.
Barangkali terminologi less-contact economy itu mengadopsi istilah less-cash society, yang muncul di awal dasawarsa 2000-an, saat Bank Indonesia memperkenalkan kampanye transaksi non tunai.
Prof. Bambang menjelaskan, less-contact economy akan efektif manakala Indonesia siap dengan peningkatan utilisasi teknologi digital.
Ia perlu didukung oleh investasi infrastruktur teknologi informasi yang menjangkau seluruh anak bangsa di pelosok Indonesia.
***
Sayangnya, belakangan ini banyak pihak latah menggunakan istilah new normal. Tak cuma latah, bahkan salah kaprah. Para pejabat pemerintah pun turut latah.
Kita sering mendengar ada rencana kebijakan tahapan-tahapan new normal. Batin saya, new normal kok ditahapkan. Aneh pula ada yang mencetuskan perlunya pelatihan new normal.
Hendak menyatakan pelonggaran PSBB, tapi yang dikatakan skenario new normal. Hendak membuka kembali mal-mal, yang disebutkan tahapan new normal.
Permainan kata-kata itu mencuatkan kesan latah, kalau tak ingin disebut bermain-main dengan istilah. Bukan pelonggaran, melainkan pengurangan PSBB. Dan kini bukan pelonggaran, tetapi new normal.
Maka tak heran kalau kemudian banyak orang bingung. Bahkan menjadikannya bahan olok-olok. Misalnya, kalau kafe dan mal boleh buka, mengapa masjid tak dibuka juga? Olok-olok semacam itu sah-sah saja.
Dunia informasi daring memungkinkan isu apa saja jadi bahan olok-olok yang berkembang dalam percakapan-percakapan virtual. Di banyak lini masa media sosial. Juga di grup-grup aplikasi pesan.
Saya tidak ingin ikutan bingung. Biasa saja. Ini memang ekses komunikasi publik new normal.
Hanya, saya bertanya-tanya, mengapa kok pemerintah ujug-ujug demen pakai istilah new normal.
Rasanya, narasi new normal dalam konteks saat ini tidaklah relevan, mengingat tujuan sebenarnya adalah mengaktifkan kembali ekonomi yang mati suri.
Banyak negara memang melakukan langkah serupa. Bahkan Presiden Donald Trump pun berulangkali ingin segera membuka kembali (reopening) ekonomi Amerika untuk menyelamatkan para pengangguran yang kini sudah mencapai 41 juta.
Buat saya, narasi kampanye new normal di Indonesia saat ini rancu dengan pembukaan kembali ekonomi. Mengapa kita tidak memakai bahasa lugas saja: ekonomi yang mati suri akan dihidupkan lagi.
Alih-alih kampanye tahapan new normal, kampanye tahapan reopening ekonomi akan lebih tepat sasaran. Apalagi bila memang pemerintah yakin, pandemi Covid-19 sudah terkendali.
Kampanye menghidupkan kembali ekonomi boleh saja dimulai dari membuka kembali mal, lantaran banyak yang kehilangan pekerjaan gara-gara malnya kelamaan nggak beroperasi. Juga sektor ekonomi lainnya, yang membuka kembali lapangan kerja.
Itu sekadar ilustrasi belaka. Jangan salah kira, bukan berarti saya setuju untuk membuka mal segera, tanpa memperhitungkan risiko penyebaran Covid-nya. Ilustrasi tersebut cuma sekadar contoh, untuk penjelasan dengan narasi yang sederhana saja.
Di banyak negara lain, reopening ekonomi memang ada prakondisinya. Mereka melakukannya setelah kasus Covid-19 mulai flattening alias melandai. Bukan di saat kasus penularan masih tinggi.
Di New Zealand, narasi reopening ekonomi dinyatakan jelas setelah tiada kasus Covid yang mendera penduduknya. Level risiko pun jelas ukuran-ukurannya. Bukan latah atau ikut-ikutan belaka.
Karenanya, bagi saya menjelaskan dengan gamblang tujuan dan tahapan re-opening ekonomi saja rasanya tidak cukup. Ini karena masyarakat butuh ketenangan secara psikologis bahwa wabah Covid-19 mulai terkendali. Tentu dengan data yang akurat dan ukuran-ukuran standard yang jelas dan transparan.
Apalagi banyak yang menduga, usia psikologis pandemi Covid-19 ini akan jauh lebih lama "menghantui" banyak orang. Wabah Covid-19 ini telah mencuci otak kebanyakan warga.
Lantaran takut virus, mereka membatasi aktivitas terbuka, bahkan ke lingkungan terdekat sekalipun.
Dalam kondisi semacam itu, tampaknya membuka mal tidak serta merta akan menggairahkan kembali ekonomi. Langkah itu perlu disertai kesungguhan pemerintah dalam menghentikan penyebaran virus Corona itu sendiri.
Untuk yang ini, bolehlah mencontoh cara China. Setelah membuka kembali ekonomi, China menerapkan sistem pelacakan pasien berbasis teknologi tracking yang efektif.
Teknologi itu bukan cuma melacak, sekaligus memantau penyebaran virus, serta menganalisis data tentang tingkat penularan dan pergerakan pasien yang terinfeksi.
Meski ada isu privasi, jika cara ini bisa diadopsi, maka langkah antisipasi pemerintah akan jauh lebih kuat. Hal itu akan memberikan ketenangan bagi masyarakat, sehingga tak perlu ketakutan untuk beraktivitas terbuka kembali, seraya menjalankan prosedur kesehatan yang selama Covid ini telah dilalui.
Sebaliknya, tanpa kesungguhan untuk memastikan bahwa wabah itu semakin terkendali, langkah membuka ekonomi boleh jadi malah akan sia-sia belaka.
Bila salah langkah, risiko dan ongkos ekonomi bisa justru lebih mahal, dan pulih dalam waktu lebih lama.
Nah, bagaimana menurut Anda?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel