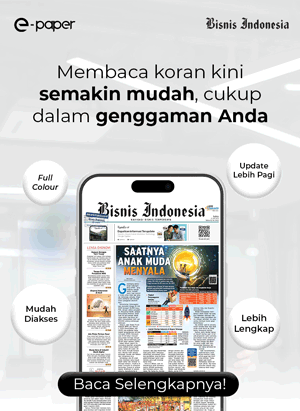Bisnis.com, JAKARTA - Sejak dirilis pertama kali pada September 2023, penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masih menyisakan sejumlah pro dan kontra.
Di satu sisi, SRBI merupakan aset derivatif yang dapat diperdagangkan. Pendalaman pasar keuangan adalah manfaat primer yang dapat diraih dari penerbitan SRBI.
Instrumen SRBI juga dapat dimiliki masyarakat umum, terutama pemain asing yang hendak bermain ‘aman’ di aset portofolio jangka pendek. Tenor SRBI 3 bulan sampai 12 bulan akan menarik masuk aliran dana asing (hot money).
Tambahan pasokan valuta asing tersebut akan mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah. Di sisi lain, perdebatan terhadap eksistensi SRBI bermula dari status sekuritisasi atas surat berharga negara (SBN) yang dipegang BI.
Tak pelak lagi, SRBI dianggap menjadi ‘pesaing’ potensial SBN. Apalagi, tenor 12 bulan yang ditawarkan SRBI ‘berhimpitan’ dengan SBN dan SPN (Surat Perbendaharaan Negara). Imbal hasil yang disediakan SRBI juga tak luput dari sorotan.
Dengan imbal hasil yang lebih atraktif dari instrumen sepantarannya, kebanyakan bank lantas memilih menempatkan dananya di SRBI dibandingkan dengan menyalurkannya ke sektor riil.
Baca Juga
Jelasnya, SRBI dicap sebagai kandidat kuat substitusi kredit. Sampai di titik itu, pro dan kontra atas keberadaan SRBI agaknya bersumber dari sudut pandang yang berbeda.
Kubu pro condong melihat penerbitan SRBI dari sisi benefit yang dapat dipetik. Sementara, pihak yang kontra terhadap eksistensi SRBI lebih menyoroti dari rambatan efek samping yang ditimbulkannya. Oleh karenanya, upaya mengonsolidasikan kedua pandangan tersebut tampaknya sulit.
Logika yang berbeda termaktub di dalamnya asumsi yang berlainan. Perbedaan asumsi menghasilkan implikasi turunan yang tidak sama. Lagi pula, tidak ada satu pun kebijakan ekonomi yang mampu menyenangkan semua pihak.
Alhasil, ikhtiar yang bisa dilakukan adalah menguji validitas kedua pandangan di atas. Kesesuaian asumsi dengan fakta niscaya menjadi modal berharga agar strategi lanjutan yang diramu menjadi lebih efektif.
Meminimisasi (alih-alih mengeliminasi) efek samping untuk mencapai tujuan yang sama niscaya lebih realistis. Sebagai contoh, motif mendapatkan imbal hasil semestinya berlaku pada kondisi sebaliknya.
Kendati imbal hasil yang ditawarkan SRBI telah menurun secara gradual, porsi perbankan dalam struktur kepemilikan SRBI masih saja lumayan tinggi. Hal semacam ini menandakan insentif SRBI bukan menjadi alibi mayor.
Kemiripan cerita agaknya terjadi pula pada kredit. Jika instrumen SRBI dianggap menjadi ‘pesaing’ potensial SBN, kepemilikan perbankan atas SRBI seharusnya menyusut saat BI mengurangi outstanding SRBI.
Langkah BI mengurangi outstanding SRBI semestinya dapat mendorong perbankan memacu pertumbuhan kredit. Data operasi moneter BI melaporkan outstanding SRBI hingga Juli 2025 tercatat menurun sebesar Rp28,9 triliun secara bulanan, atau secara ekuivalen menyusut Rp169,4 triliun secara tahunan.
Meskipun likuiditas perbankan meningkat, efeknya terhadap akselerasi penyaluran kredit belum terlihat kuat. Hasil Survei Perbankan BI juga mengonfirmasi. Pertumbuhan kredit anyar pada triwulan II/2025 meningkat dibanding triwulan sebelumnya.
Namun, secara tahunan, pertumbuhan kredit justru melambat dari 9,6% pada Januari menjadi 7,6% pada Juni 2025. Asimetrisitas semacam ini memvalidasi SRBI bukan substitut kredit.
Bahwa kenaikan likuiditas dari pelepasan SRBI belum sepenuhnya tersalurkan dalam bentuk kredit adalah cerminan sikap perbankan yang masih hati-hati. Tesis itu tidak mengada-ada.
Indeks Lending Standard (ILS) masih berada di level positif 0,08, yang mengindikasikan bank tetap selektif dalam pemberian kredit.Dari sisi jenis kredit, hanya kredit konsumsi yang mencatat pertumbuhan stabil.
Sebaliknya, kredit modal kerja melambat menjadi 4,3% dan kredit investasi tumbuh 12,2%, turun tipis dibanding bulan sebelumnya. Artinya, preferensi risiko perbankan masih konservatif, hanya menyasar pada sektor ekonomi tertentu.
Alhasil, pengurangan out-standing SRBI yang tidak serta merta diikuti dengan peningkatan penyaluran kredit menunjukkan keduanya independen. Tidak ada korelasi dan simetri-sitas antara keduanya. Dugaan awal bahwa keduanya substitusi berpangkal dari fungsi utama intermediasi yang diemban perbankan.
SRBI dan kredit sejatinya bisa juga komplementer jika perbankan mampu menjalankan fungsinya sebagai agen kebijakan moneter bank sentral. Dengan argumen itu pula, kepemilikan perbankan atas SRBI justru mengindikasikan kegagalan perbankan dalam menunaikan amanat penjualan SRBI, khususnya, kepada pemain asing.
SRBI (termasuk SVBI dan SUVBI) tampaknya masih akan diterbitkan BI selama pasokan obligasi di Tanah Air belum mampu memenuhi permintaan.
Dengan demikian, instrumen SRBI menuntut BI berinovasi dalam strategi penerbitannya yang disesuaikan dengan konteks dan variasi tantangan yang akan dihadapi.Perbankan sendiri juga harus mawas diri agar pas menempatkan diri dalam ekosistem yang terus berkembang.
Fungsi intermediasi keuangan dan agen kebijak-an moneter harus dibedakan sungguhpun tidak terpisahkan. Substitusi antara SRBI dan kredit perbankan muncul dari penggabungan makna kedua fungsi tersebut.
Dengan menyandarkan diri kembali utuh pada intermediasi keuangan dan agen kebijakan moneter, pro dan kon-tra SRBI niscaya tidak akan timbul lagi. Masing-masing toh memiliki karakteristik yang berlainan. Pada akhirnya, SRBI dan kredit per-bankan bisa berjalan seiring tanpa meninggalkan salah satunya.
Bukan begitu?